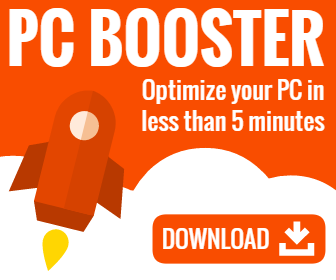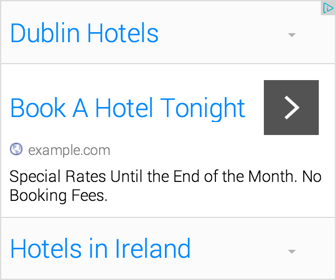AKU berdiri di depan sekolah tempatku mengajar lebih dari dua puluh tahun. Kupandangi setiap murid yang berjalan pulang satu per satu dari gerbang sekolah. Di wajah mereka, kulihat masa depan bangsa ini, masa depan kota ini. Generasiku gagal menjauhkan kota ini dari kemiskinan, kriminalitas, perjudian, dan peredaran narkoba yang semakin merajalela. Tapi aku yakin, mereka yang saat ini berseragam sekolah di hadapanku, kelak akan memperbaiki semua masalah di kota ini. Berastagi masih punya harapan.
Udara dingin kota ini mulai menusuk tubuhku. Aku masih terpaku memandangi mereka. Terkadang, aku melemparkan senyum pada mereka yang menatap ke arahku. Lewat senyum itu, kutitipkan pesan pada mereka agar tetap semangat menjalani hari-hari mereka sebagai pelajar. Masa penempaan yang tentu melelahkan bagi mereka.
Di tangan kiriku, kugenggam buku tebal berwarna kuning-kitab suci pribadiku. Buku kumpulan tulisan ide-ide Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, yang diterbitkan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. Dari buku ini aku belajar banyak hal, salah satunya bahwa menjadi guru bukanlah sekadar pilihan pekerjaan. Menjadi guru berarti siap memikul beban besar bernama masa depan bangsa.
Sejenak aku teringat pada masa-masa awal aku mengajar di sekolah ini. Saat aku belum mengenal buku yang kini kugenggam. Saat itu baru setahun setelah aku lulus dari perguruan tinggi keguruan ternama di Sumatera. Aku hanya seorang sarjana yang terpaksa kuliah di jurusan pendidikan, yang mau tidak mau harus menjadi guru.
Jangankan mengenal konsepsi pendidikan yang dirumuskan Ki Hadjar Dewantara, kala itu aku menganggap mengajar hanyalah jalan hidup yang harus kutempuh. Tanpa pengetahuan cara mengajar yang baik, aku hanya meniru cara guruku waktu sekolah dulu atau guru-guru senior di sekolah ini.
Tak jarang aku merokok sambil mengajar, seperti yang dilakukan salah seorang guru senior.
“Yang penting pintu kelasnya dibuka, biar asapnya bisa keluar,” ucapnya saat kutanya apakah boleh merokok di ruang kelas.
Aku juga sering menghukum murid dengan menjemur mereka di lapangan. Bahkan, saat emosiku memuncak, pernah sekali telapak tanganku terpaksa mendarat di pipi mereka.
Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal kitab suci pribadiku. Pertemuanku dengan buku ini juga sangat membekas. Waktu itu, aku merasa benar-benar tertekan dengan pekerjaanku sebagai guru, muak dengan semua tingkah laku murid-muridku. Di tengah aku mencari buku tentang kesehatan mental di salah satu toko buku kecil di Medan, aku melihat buku ini terselip di tumpukan buku-buku lama yang mulai berdebu. Warnanya yang mencolok langsung menarik perhatianku.
Aneh memang, buku ini tidak pernah dibahas di kampusku dulu. Bahkan, semua guru yang mengajar di sekolah ini pun tidak mengetahuinya. Kita hanya mengagungkan Ki Hadjar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan, tanpa pernah mengenal ide-idenya tentang pendidikan.
Salah satu isi buku ini yang menamparku adalah bagaimana beliau menjelaskan perihal menghukum murid. Menurut beliau, hukuman mestinya diniatkan untuk memperbaiki kesalahan siswa.
“Hukuman harus selaras dengan kesalahannya. Maka dari itu, hukuman seperti misalnya harus menulis lima puluh kali perkataan ‘aku tidak boleh datang kasip (terlambat)’, berdiri satu jam di belakang papan tulis, hukuman memukul dengan rotan dsb. Itulah hukuman yang bersifat siksaan, pembalasan, dengan kekejaman dari guru kepada murid. Lama kelamaan si murid akan kehilangan kecintaannya kepada guru, karena merasa tidak dicintai olehnya.”
Betapa aku merasa kolot, ketika tahu Ki Hadjar menulis ini di tahun 1929, dan aku masih menghukum murid dengan menyuruhnya berdiri, bahkan di lapangan upacara.
Sejak itu aku selalu memilih hukuman yang sesuai untuk kesalahan yang dilakukan murid. Misalnya jika ada murid yang datang terlambat, aku menghukumnya dengan menyuruhnya membuat rencana jadwal harian untuk seminggu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari hukuman itu, aku berharap si murid bisa lebih baik dalam mengatur waktu, sehingga tidak telat lagi. Hanya dari satu poin, aku sudah belajar banyak. Bayangkan jika aku bisa menerapkan seluruh isi kitab ini.
Ya, meskipun guru-guru lain masih tetap sama. Setiap kali aku berusaha menjelaskan pemikiran Ki Hadjar kepada mereka, selalu saja berakhir dengan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Tapi ini tidak akan lama lagi. Jika sesuai rencanaku, tahun ajaran yang akan datang, aku akan menjadi kepala sekolah. Aku yakin, dengan posisi itu, aku bisa menerapkan pemikiran Ki Hadjar secara lebih masif, minimal di sekolah ini.
Aku menarik napas panjang, masih menatap ke arah sekolah. Murid dan guru yang keluar dari gerbang itu semakin sedikit, mungkin hanya tersisa beberapa orang lagi. Aku tersenyum kecil.
* * * * * * *
Pria itu masih berdiri di seberang sekolah, meski tak ada lagi murid yang berjalan keluar. Hanya tersisa seorang satpam yang beberapa kali melirik ke arahnya. Di balik gerbang sekolah, satpam itu berdiri menunggu seluruh murid keluar, agar dia bisa menutup gerbang. Tinggal tiga orang murid yang sedang dihukum menghormat bendera di lapangan upacara. Mereka dihukum karena tidak mengerjakan PR Matematika. Satpam yang baru bekerja dua minggu itu sudah mulai hafal kebiasaan Pak Romi dalam memberi hukuman.
Tak lama Pak Romi muncul dari ruang guru, melangkah menuju lapangan upacara. Setelah terdengar sedikit bentakan, ketiga murid itu langsung berjalan cepat menuju kelas, mengambil tas mereka, lalu bergegas ke arah gerbang.
Si satpam tampak lega, bisa segera pulang saat melihat ketiga murid itu berjalan mendekat.
“Besok kerjakan PR, ya. Biar enggak dijemur lagi sama Pak Romi,” ucapnya setengah meledek.
Mereka hanya menatap si satpam dengan wajah merah padam, berlalu tanpa sepatah kata pun. Di belakang mereka, menyusul Pak Romi yang juga berjalan mendekat.
“Maaf agak lama ya, Pak. Saya sengaja biar mereka enggak kebiasaan.”
Pak Romi menyulut rokok yang sedari tadi terselip di bibirnya. Ini pertama kalinya dia mengajak satpam baru itu berbincang.
“Aman, Pak. Memang harus dikerasin anak-anak kayak gitu.”
Pak Romi tersenyum, perlahan asap keluar dari sela-sela senyumannya. Sejenak dia memandang ke arah seberang sekolah. Senyumnya tiba-tiba luntur.
“Itu siapa ya, Pak?” tanya si satpam.
“Hampir tiap hari saya perhatikan, dia selalu berdiri di sana, senyum-senyum sendiri. Takutnya punya niat jahat. Kalau perlu biar saya usir.”
Pak Romi menarik napas panjang, matanya redup. “Itu Pak Rinto, dia dulu juga guru di sini, Pak.” Kalimatnya tertahan, dihisapnya rokoknya lambat. “Tapi dia terlalu keras kepala. Terlalu percaya diri bisa mengubah segalanya. Padahal dia hampir jadi kepala sekolah. Tapi guru-guru lain enggak suka caranya, akhirnya gagal.”
Si satpam melirik pria itu lagi, “Terus, Pak?”
“Dia jadi gila.”
Si satpam mengangguk pelan. Diperhatikannya pria di seberang itu berjalan menjauh. Di tangan kirinya, tergenggam sebuah karton kuning yang tampak lusuh. Di karton itu terpajang sebuah foto. Foto yang tampak familiar. Mungkin salah satu pahlawan yang pernah dia lihat di ruang kelas, pikirnya.